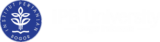Titik Kritis Dan Mitigasi Problem Budidaya Udang

Titik Kritis Dan Mitigasi Problem Budidaya Udang
Oleh: Mohammad Rakha Syahla Dewangga
Udang merupakan komoditas akuakultur yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah untuk terus tingkatkan produksinya. Terdapat tiga jenis udang yang dibudidayakan di Indonesia yaitu udang windu (Penaeus monodon), udang galah (Macrobrachium rosenbergi) dan udang vaname (Litopenaeus vannamei). Namun dalam dua dekade terakhir udang vaname menjadi komoditas unggulan Indonesia. Menurut data FAO (2022) Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka produksi udang terbesar ke-dua di dunia dengan total produksi yaitu 14,8 juta ton. Angka tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara China yang menduduki peringkat pertama sebagai penghasil udang terbesar di dunia dengan total produksi yaitu 70 juta ton. Melihat perbedaan yang cukup signifikan jaraknya tentu harusnya mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan jumlah produksinya dengan menambah jumlah kolam atau tambak dan memperhatikan sarana prasarana yang dibutuhkan para petambak dalam produksi udang.
Apa saja kendala yang dialami pada budidaya udang?
Dalam produksinya di lapangan tentunya terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh para pembudidaya. Contohnya seperti perihal genetik udang yang akan berimplikasi pada peningkatan tumbuh kembang udang, sanitasi atau sumber air yang kurang bersih, munculnya hama penyakit pada udang dan perubahan iklim. Tepatnya pada satu bulan terakhir perubahan kondisi suhu yang terjadi pada beberapa bagian di Pulau Jawa menyebabkan penurunan suhu dan berimplikasi pada suhu air kolam budidaya udang. Hal tersebut menjadi warning bagi para pembudidaya udang terhadap masuknya potensi penyakit yang akan terjadi.
Belakangan ini yang sangat menjadi perhatian para pembudidaya yaitu serangan penyakit WSSV atau White Spot Syndrome Disease, serta AHPND atau Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease. Serangan penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menghuni perairan dengan tingkat salinitas sedang dan tinggi, seperti perairan payau dan laut. Bakteri vibriosis merupakan patogen yang bertanggung jawab terhadap kematian udang yang dialami oleh para petambak atau pembudidaya di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini berdampak buruk terhadap tingkat produksi udang di Indonesia. Maka tidak heran jika target pemerintah dalam soal produksi udang mengalami penurunan saat virus ini masuk ke lingkungan budidaya.
Kenali lebih lanjut virus pada udang!
White Spot Syndrome Virus (WSSV) dan Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) merupakan contoh dari sekian penyakit yang tercatat menjadi penyebab matinya ratusan bahkan ribuan udang di setiap tambak di Indonesia. WSSV atau penyakit bitnik putih pada udang pertama kali tercatat terjadi di Taiwan pada tahun 1992. Selanjutnya penyakit ini muncul di Indonesia pada tahun 1994. Sejak saat itu WSSV menjadi penyakit yang sangat dihindari oleh para petambak. Sebab sejak tanda-tanda infeksi muncul, dalam kurun 3-10 hari virus ini mampu menyebabkan kematian masal hingga 100% (Wittefeldt et al. 2004). Penyakit ini ditandai dengan munculnyya bitnik putih pada karapas udang, nafsu makan turun dan udang berenang dipermukaan serta pinggiran kolam.
AHPND disebabkan oleh bakteri Vibrio parahaemolyticus yang umum menyerang udang pada fase dewasa. Baik dari stadia nauplii, zoea, mysis hingga post-larvae turut terjangkit oleh penyakit AHPND. AHPND menjadi momok menakutkan dikalangan petambak udang sebab penyakit ini mampu menyebabkan kematian masal hingga 80% di negara China (Yuhana dan Afiff 2023). Gejala yang umum terlihat pada udang yaitu warna tubuh yang pucat, kosongnya saluran pencernaan dan hepatopankreas tampak mengecil. Kerugian yang amat sangat besar menjadi risiko yang dihadapi jika para petambak udang dihadapkan dengan persoalan AHPND dan ikan yang terinfeksi AHPND dapat meyebabkan penyakit jika tertelan oleh manusia (Lee et al. 2015).
Terinfeksinya udang oleh WSSV dikarenakan oleh perubahan salinitas pada air. Perbedaan tekanan osmotik yang menyebabkan proses osmoregulasi atau pengaturan keluar dan masuknya cairan ke dalam sel yang menjadi terganggu (Amrillah et al. 2015). Perubahan tersebut dapat memicu masuknya virus. Hal ini dapat diatasi dengan memasukkan air laut melalui saluran inlet secara berangsur-angsur dengan debit air yang rendah jika terjadi penurunan salinitas. Blooming plankton, penurunan kadar oksigen, fluktuasi pH, dan perubahan suhu air dapat menjadi penyebab lain mewabahnya WSSV (Yanti et al. 2017). Blooming plankton dapat diatasi dengan penurunan dosis pupuk (seperti molase) yang diberikan ke kolam. Penurunan kadar oksigen terlarut (DO) dapat dikontrol pada malam hari yang notabene akan turun saat malam hari. Jika penurunan DO terjadi selama 3-4 hari, maka harus dilakukan panen parsial untuk mengurangi biomassa di dalam kolam karena carrying capacity yang sudah tidak mendukung akibat tebaran benur yang terlalu padat. Fluktuasi pH dapat diatasi dengan pemberian kapur sesuai dosis yang disarankan untuk menjaga stabilitas nilai pH. Perubahan suhu dapat di atasi dengan memasukkan air jika suhu tinggi dan mengeluarkan air jika suhu rendah.
Fluktuasi suhu, pH dan salinitas juga menjadi penyebab udang terjangkit AHPND, sebab bakteri V. parahaemolyticus dapat berkembang dan tumbuh dengan bergantung pada kandungan karbon, kondisi suhu, konsentrasi oksigen, kadar pH dan salinitas yang bervariasi. Hal tersebut menyebabkan V. parahaemolyticus dapat tinggal pada kondisi lingkungan yang berbeda-beda (Soto-Rodriguez et al. 2019).
Bagaimana solusinya?
Munculnya kedua penyakit tersebut tidak lain merupakan dampak dari sanitasi atau kualitas air yang buruk di dalam kolam budidaya. Sebab terinfeksinya udang merupakan kombinasi dari stressor lingkungan yakni kualitas air yang buruk dengan adanya inang atu udang di kolam. Pada hakikatnya, patogen memang selalu ada di lingkungan budidaya. Akan tetapi, ketika kualitas air baik parameter fisika, kimia, maupun biologi mengalami penurunan dan berada pada kondisi kritis, maka saat itulah penyakit mampu masuk dan menjangkit udang.
Oleh karena itu, manajemen kualitas air perlu diperhatikan lebih rinci dan terus dimonitor setiap hari melalui pemeriksaan harian atau mingguan. Beberapa parameter yang harus diperiksa yaitu fisika (suhu kecerahan, warna); kimia (pH, Dissolved Oxygen (DO), nitrat, fosfat, Total Ammonia Nitrogen (TAN), alkalinitas, Total Organic Matter (TOM), kesadahan); dan biologi (total bakteri, total vibrio, dan kelimpahan plankton). Nilai beberapa rincian parameter tersebut seyogyanya harus berada pada titik optimum dan berkiblat pada Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai nilai optimum serta batas maksimum dan minimum kualitas air budidaya.
DAFTAR PUSTAKA
Amrillah AM, Widyarti S, Kilawati Y. 2015. Dampak stres salinitas terhadap prevalensi White Spot Syndrome Virus (WSSV) dan survival rate udang vannamei (Litopenaeus vannamei) pada kondisi terkontrol. Research Journal of Life Science. 2015. 2(2):110-23.
Lee JM, Lee WJ, Kim MJ, Cho YS, Lee JS, Lee HJ, Yoon SW, Kim KS. 2015. Comparative evaluation of the VITEK 2 system and speciesspecific PCR methods for the detection of vibrio species isolated from shrimp. Journal of Food Hygiene and Safety. 30(3). 281-288.
Soto-Rodriguez S, Lozano-Olvera R, Palacious-Gonzales DA, Bolan-Mejia C, Rendon Anguilar KG. 2019. Characterization and growth conditions of Vibrio parahaemolyticus strains with different virulence degrees that cause acute hepatopancreatic necrosis disease in Litopenaeus vannamei. Journal of the World Aquaculture Society. 50(5): 1002-1015.
Wittefeldt J, Cifuentes CC, Vlak JM, Van Hulten MCW. 2004. Protection of Penaeus monodon against white spot syndrome virus by oral vaccination. Journal Virology. 78(4): 2057-2061.
Yanti ME, Herliany NE, Negara BF, Utami MA. 2017. Deteksi molekuler White Spot Syndrome Virus (WSSV) pada udang vaname (Litopenaeus Vannamei) di PT. Hasfam Inti Sentosa. Jurnal Enggano. 2(2): 156-169.
Yuhana M, Afiff U. 2023. Mini-review: Utilization of Vibrio parahaemolyticus virulence coding genes for early detection of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND). Jurnal Akuakultur Indonesia. 22(1): 87-96.
BIODATA PENULIS
Penulis artikel ini bernama Mohammad Rakha Syahla Dewangga. Saat ini penulis berkuliah di Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University angkatan 58. Penulis aktif dalam beberapa kegiatan di kampus, mulai dari organisasi, kepanitiaan dan kegiatan pengabdian di bidang pendidikan.